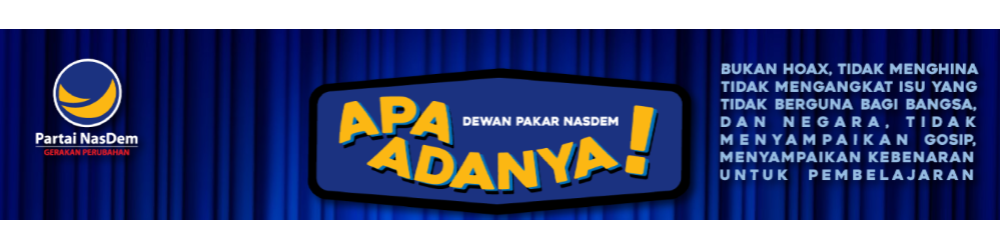Mengapa Indonesia Sulit Maju
Elwin Tobing
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem
Bulan lalu, artikel singkat saya tentang mengapa Tiongkok melesat dalam tiga dekade terakhir sempat viral. Jawabnya sederhana: relentless pursuit of knowledge—semangat mengejar ilmu tanpa henti. Pepatah lama berkata, “kejarlah ilmu sampai ke negeri tirai bambu.” Menariknya, Cina justru memegang prinsip sebaliknya: kejarlah ilmu sampai ke Paman Sam. Suka atau tidak, Amerika Serikat masih menjadi pusat pengetahuan dunia.
Seperti saya tulis dalam artikel tersebut, jumlah mahasiswa Cina di AS melonjak dari 37.000 pada 1990 menjadi 370.000 pada 2019. Tanpa pandemi dan tensi geopolitik, angka itu mungkin melewati 450.000—sekitar 45% dari total mahasiswa internasional di Amerika Serikat (AS)
Tahun 2019, 25 dari setiap 100 ribu warga Tiongkok kuliah di AS. Dari Indonesia? Hanya sekitar 8.300 atau 3 dari 100 ribu penduduk Indonesia yang belajar di AS. Ini bukan sekadar angka—ini cerminan lemahnya semangat mengejar ilmu di Indonesia.
Akar masalahnya? Rendahnya budaya membaca. Pengejaran pengetahuan dimulai dari membaca. Seperti kata penulis buku anak-anak tersohor, Dr. Seuss: “The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.”
Kutipan ini merangkum kekuatan membaca sebagai pintu menuju pengetahuan, pertumbuhan, dan berbagai kemungkinan tanpa batas. Sayangnya, kemampuan membaca di Indonesia sangat rendah.
Pada 2022, 75% siswa usia 15 tahun hanya mencapai Level 2 atau lebih rendah (dari 6 level) dalam kemampuan membaca. Tren ini sudah berlangsung lebih dari dua dekade. Pada 2014/15, OECD (Organisasi Negara Maju) melakukan survei di 33 negara tentang Program Penilaian Kompetensi Orang Dewasa usia 16-65 tahun. Indonesia termasuk dalam survei dan penilaian dilakukan dengan sampel di Jakarta. Hasilnya? Sekitar 69% pekerja memiliki kemampuam membaca Level 1 atau lebih rendah. Artinya hanya mampu memahami teks dasar.
Itu di Jakarta. Secara nasional, angkanya kemungkinan lebih tinggi, bahkan di atas 80%. Temuan ini menunjukkan 80% lebih orang dewasa Indonesia masih kesulitan memahami teks kompleks yang penting untuk berpartisipasi efektif dalam masyarakat modern.
Bayangkan, berapa banyak dari mereka yang kini berada di posisi pengambil keputusan? Ini hanya satu sisi. Jika diperluas, terlihat kemalasan yang lebih dalam: malas berpikir, malas bekerja keras, malas berkolaborasi. Yang rajin? Rapat. Kadang berjam-jam, tanpa hasil nyata.
Rapat dianggap solusi. Padahal sering untuk menambah masalah. Fokusnya bukan pada solusi, tapi pada pengulangan masalah. Tidak mengherankan bila pengambilan keputusan jarang berbasis data atau analisis mendalam. Itu perlu membaca dan belajar serius.
Di sisi lain, semangat pura-pura tinggi. Kita belum bicara karakter? Itu masalah besar lainnya. Tetapi, itu juga terkait dengan lemahnya budaya membaca.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) subur di tengah budaya malas dan rendahnya semangat mencari ilmu. Di negara maju, KKN lebih rendah bukan hanya karena hukum ditegakkan, tapi karena budaya yang cenderung menolak praktik tersebut. Rakyat melihat bahwa kemajuan dirinya bisa tercapai jika belajar dan bekerja keras. Jika budaya permisif terhadap KKN, hukum pun akan ikut terjerat.
Tanpa terobosan, kita terjebak dalam lingkaran setan. Lupakan “Indonesia Emas.” Yang ada: Indonesia lemas—dan cemas. Solusinya? Mulai dari membaca. Karena itu, tiga tahun terakhir saya menggagas kampanye nasional Reading for the Future (RFF). Misinya membangun budaya baca melalui program terarah, kolaboratif, dan melibatkan semua pihak.
RFF bukan sekadar kampanye. Ini gerakan nasional. Sasarannya: anak-anak dan remaja. Karena dari merekalah masa depan dibentuk—dengan karakter, kecerdasan, dan daya pikir kuat.
Mari bangun bangsa pembaca. Untuk anak-anak Indonesia. Untuk masa depan Indonesia.